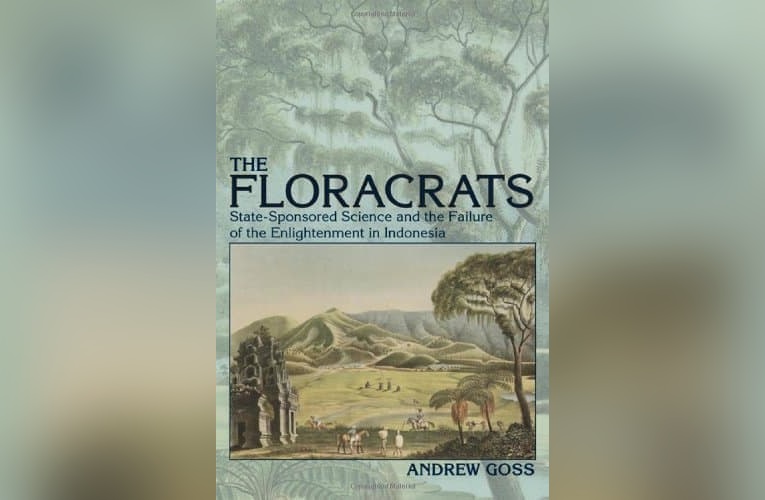hancau.net – Jika kita memiliki kesempatan untuk berkunjung ke perpustakaan Universitas Michigan di Amerika Serikat. Di salah satu lorong terdapat jurnal penelitian biologi dari Hindia Belanda. Di sebelah tumpukan buku ilmiah dan selebaran tentang alam Indonesia di era 1840an.
Pada tahun 1997 sejarawan Adrew Goss berdiri di lorong ini. Ia menyadari bahwa di tahun 1900an, kualitas jurnal, khususnya jurnal biologi. Dari lembaga penelitian di Indonesia tidak kalah dengan lembaga-lembaga di Boston, London, dan Berlin. Dulu kualitas jurnal penelitian kita kelas dunia.
Sebelumnya, CEO Bukalapak Achmad Zaky sempat mengirim cuitan tentang anggaran riset dan pengembangan di Indonesia. Ia bercuit, bahwa Indonesia sangat tertinggal dari banyak negara lain.
Di tingkat global, kita juga jarang sekali mengenal ilmuwan Indonesia yang menghasilkan penelitian. Apalagi temuan ilmiah yang dikenal luas. Lalu apa yang terjadi dalam satu abad terakhir?
Kualitas jurnal penelitian dan produksi ilmu pengetahuan di Indonesia seolah mundur ke belakang.
Pada tahun-tahun menjelang kemerdekaan India. Jawaharlal Nehru, dari dalam penjara tempat ia ditahan. Membayangkan suatu masyarakat modern. Masyarakat dengan kebudayaan dan agama yang sudah sangat kuat. Serta di dalam DNA kebudayaan bangsa India, dapat dikawinkan dengan suatu budaya berdasarkan logika.
Budaya dimana ilmu pengetahuan menjadi dasar bagaimana suatu peradaban dibangun. Ia menyebut ini sebagai Scientific Temper atau perangai ilmiah.
70 tahun kemudian
Kita nyalakan televisi. Kemudian, kita lihat orang-orang yang diundang sebagai “ahli” atau “pakar” bukanlah orang-orang yang memiliki penguasaan terhadap data dan informasi berdasarkan logika. Mereka selalu menyuguhkan narasumber-narasumber yang pandai bersilat lidah. Namun belum tentu disiplin dalam logika yang dia gunakan.
Di dalam buku yang berjudul FLORACRATS. Seorang sejarawan bernama Andrew Goss berargumen. Pendekatan terhadap ilmu pengetahuan di Indonesia hari ini memiliki akar yang bisa ditarik kepada kolonialisme. Serta bagaimana pemerintah Hindia Belanda saat itu berusaha mengontrol perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
Saat itu pemerintah kolonial yang sangat paternalistik dan birokratis mengkooptasi ide-ide atau gagasan inovasi berbasis ilmu pengetahuan. Tentu saja demi memaksimalkan profit dari perdagangan rempah-rempah.
Ada 4 babak sejarah berkembanganya ilmu pengetahuan di Indonesia
Periode Kolonial
Pada tahun 1480, seorang botanist dari Belanda yang bernama Melchior Treub ditugaskan untuk datang ke Indonesia. Ia bertugas mengelola Botanical Garden of Buitenzorg. Sekarang kita sebut dengan nama “Kebun Raya Bogor”.
Treub memiliki dua misi utama.
Pertama, bagaiman Kebun Raya Bogor bisa diangkat statusnya secara internasional. Sehingga menjadi pusat perkembangan botani dan juga national history di dunia pada saat itu.
Kedua, beliau juga diminta agar ilmu pengetahuan yang dihasilkan adalah ilmu yang memiliki nilai ekonomi. Artinya ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda dalam proses perdagangan mereka.
Sebagai hasilnya, kebijakan-kebijakan yang didorong oleh Treub adalah kebijakan yang mengontrol produksi ilmu pengetahuan.
Sebagai contoh, para botanis dan ahli national history pada saat itu. Mereka direkrut untuk dijadikan pegawai pemerintah. Andrew Goss menyebutnya sebagai “Floracrats”. Yakni “Flora Tecnocrats”.
Para ahli botani yang ditanamkan semacam DNA teknokrat kemudian berorientasi pada proyek pemerintah.
Pada kesempatan lain. Para ilmuwan asli Indonesia di tim Treub, merasa ingin mengangkat derajat saudara sebangsanya. Tentu saja dengan adanya penyebaran ilmu pengetahuan.
Treub melihat ini sebagai kesempatan untuk mendirikan apa yang kita tahu sekarang sebagai Institut Pertanian Bogor.
Periode Revolusi
Ini adalah masa menjelang kemerdekaan Indonesia dan setelahnya.
Pada periode ini terdapat suatu pendekatan yang disebut sebagai “Desk Science”. Dimana ilmu pengetahuan murni harus dihubungkan secara langsung dengan proses pembangunan nasional.
Di satu sisi, ini memastikan bahwa negara pasti akan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendorong penelitian. Hal ini kemudian mendorong prioritas agenda nasional.
Namun di sisi lain, kita tahu bahwa di periode ini ilmu pengetahuan di Indonesia bukanlah ilmu pengetahuan kelas dunia.
Di dalam bukunya, Andrew Goss juga berargumen bahwa para ilmuwan Indonesia tidak berperan dalam proses perebutan kemerdekaan. Disebabkan karena kedekatan mereka sebagai birokrat kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu.
Salah satu proyek ilmu pengetahuan yang saat itu terjadi adalah Flora Malesiana. Merupakan proses mensintesiskan deskripsi tentang apa saja tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia.
Kita bisa melihat ini bukanlah sebuah pendekatan yang mendorong lahirnya biologi khas Indonesia. Akan tetapi, suatu organisasi pengetahuan yang diarahkan untuk kepentingan proses pembangunan negara.
Kita juga bisa melihat bahwa pemerintah berusaha menginstitusionalkan proses produksi ilmu pengetahuan. Dengan mendirikan apa yang kita tahu sebagai MIPI (Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia). Kemudian berkembang menjadi LERENAS dan DURENAS.
Periode Orde Baru
Hampir sama dengan periode kolonial di Indonesia. Pemerintahan rezim orde baru juga memiliki kepentingan untuk mengontrol proses produksi ilmu pengetahuan. Baik itu yang sifatnya ilmiah maupun sosial.
Akhirnya kita melihat bahwa akademisi bukanlah ilmuwan, tetapi justru teknokrat. Orientasi produksi ilmu pengetahuan juga sangat berbasis proyek atau pesanan pemerintah.
Untuk ilmu pengetahuan alam. Kita tahu bahwa ada LIPI yang didirikan pada tahun 1967, dan juga BPPT pada tahun 1974. Ilmu pengetahuan murni dan terapan diorganisasikan oleh pemerintah sedemikian rupa untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.
Hal yang menarik untuk dibahas ialah cabang ilmu sosial. Analisis berbasis kelas atau relasi kekuasaan disingkirkan oleh pemerintah. Kemudian diisi oleh akademisi-akademisi yang lebih pro rezim. Baik itu secara ideologi maupun politik.
Akhirnya, banyak jurnal penelitian yang dihasilkan lebih berfokus kepada investasi, pertumbuhan ekonomi, dan industri.
Tidak ada penelitian yang membahas tentang perebutan tanah, operasi oleh rezim, ataupun analisis berbasis kelas lain, termasuk diskriminasi.
Kita sama-sama tahu, pemerintah orde baru melakukan sensorship terhadap istilah yang bisa digunakan sebagai instrumen analisis.
Kata buruh diganti dengan golongan pekerja atau karyawan. Kemudian tiong hoa diganti dengan cina. Miskin atau proletar diganti dengan golongan berpenghasilan rendah, dan sebagainya.
Sehingga, hasilnya produksi ilmu sosial yang terjadi pada periode orde baru terasa hampa. Baik itu secara politik dan tidak memiliki kekuatan analisis yang kritis.
Periode Sekarang
Lalu bagaimana kondisi ilmu pengetahuan saat ini?
Apakah pemerintah sudah cukup memainkan peran yang sehat? dimana pemerintah menyediakan ruang dan sumber daya yang cukup bagi para ilmuwan.
Kemudian seberapa jauh pemerintah mengontrol atau membatasi proses produksi ilmu pengetahuan?
Menurut Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden, dirinya merasa berkewajiban dan bahkan terobsesi mendorong pembuatan kebijakan yang lebih rasional.
“Akademisi kita, tidak cukup banyak yang mau mengkomunikasikan penelitiannya di level dunia dengan bahasa mereka di outlet mereka, berargumen tentang Indonesia”. (fix)